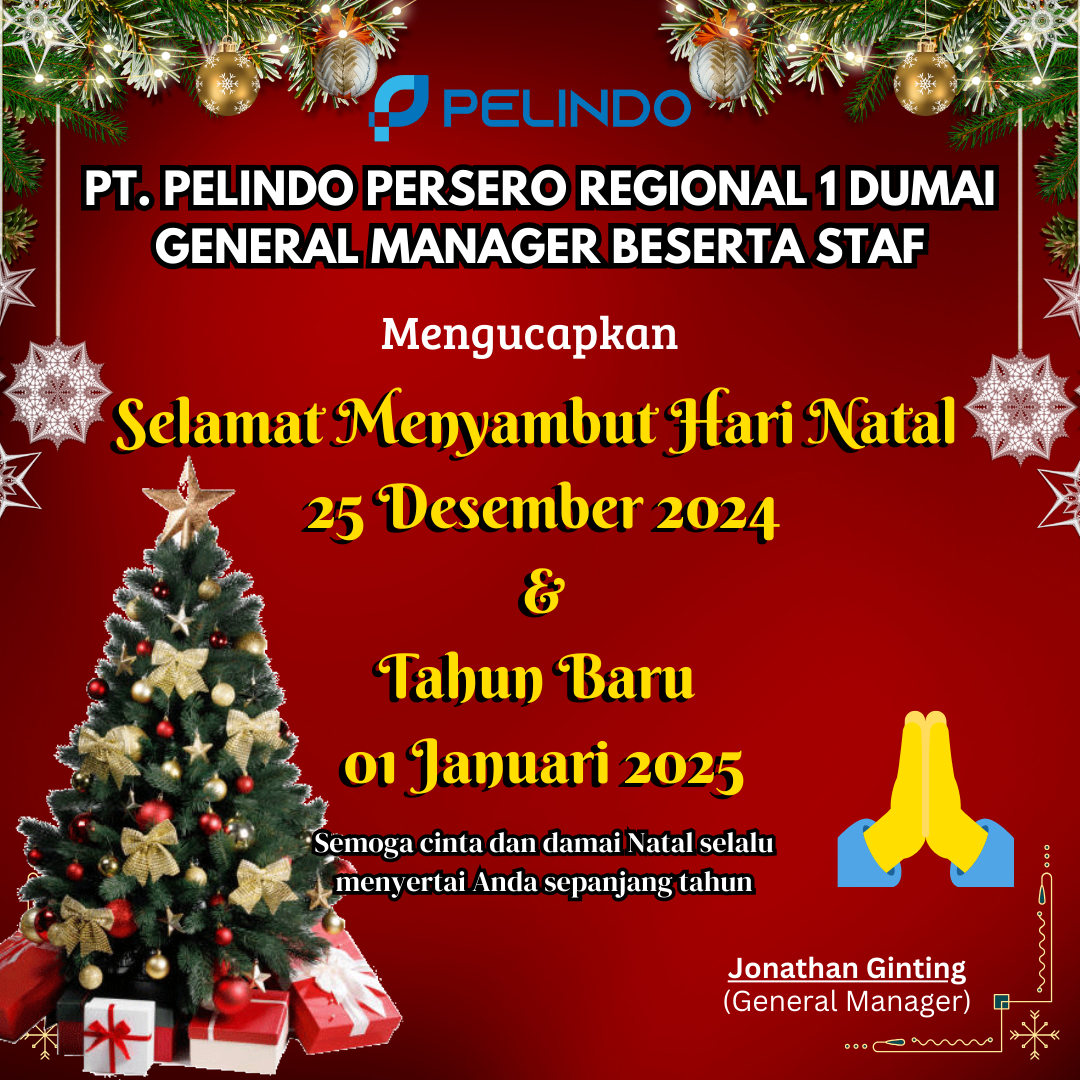Identitas Keagamaan dan Pesantren Tasikmalaya: Aktor Geopolitik yang Sering Terlupakan
Oleh : Nabila Zein Amalia
Mahasiswi Program Studi Ilmu Politik,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.
Ketika orang membicarakan geopolitik, biasanya yang terbayang adalah isu besar seperti perebutan pengaruh antarnegara, jalur maritim, atau hubungan kekuatan global. Padahal geopolitik juga bekerja di tingkat lokal. Dalam konteks Tasikmalaya, identitas keagamaan dan jaringan pesantren memiliki peran geopolitik tersendiri yang sering tidak disadari. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat kekuatan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memengaruhi arah perkembangan daerah.Colin S. Gray menggambarkan bahwa geopolitik adalah seni mengelola kekuatan dalam ruang yang terus berubah. Gray melihat bahwa kekuatan tidak hanya berada pada negara atau militer, tetapi juga pada aktor lokal yang punya pengaruh sosial. Prinsip ini relevan untuk memahami pesantren sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan masyarakat, membentuk pandangan politik, dan menentukan dinamika sosial di Tasikmalaya.Selain itu, doktrin Wawasan Nusantara yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR IV/MPR/1999 menekankan pentingnya kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip ini relevan dengan peran pesantren yang menjadi simpul budaya dan sosial masyarakat Tasikmalaya. PP No. 37/2002 dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, meski tampak jauh dari konteks pesantren, sebenarnya menegaskan cara pandang bahwa seluruh ruang Indonesia darat, laut, dan masyarakatnya harus dikelola sebagai satu kesatuan. Prinsip kesatuan inilah yang menjadikan pesantren bagian dari stabilitas lokal dalam kerangka geopolitik nasional.Tasikmalaya sering disebut sebagai “kota santri” karena jumlah pesantren yang banyak dan kuatnya identitas keagamaan. Kehadiran pesantren membentuk pola budaya masyarakat, mempengaruhi nilai-nilai, dan menciptakan jaringan sosial yang mengakar. Kyai memiliki posisi sebagai pemimpin moral, tempat orang meminta nasihat, serta tokoh yang dihormati dalam urusan sosial dan politik. Banyak penelitian tentang pesantren di Jawa Barat menunjukkan bahwa identitas keagamaan ini menjadi modal sosial yang besar bagi masyarakat. Identitas tersebut bukan sekedar memupuk solidaritas dan ketahanan sosial, tetapi juga memberi pesantren posisi strategis dalam dinamika politik lokal.Dalam arena politik, kyai dan pesantren memiliki pengaruh besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kyai sering menjadi rujukan politik masyarakat, terutama dalam menentukan pilihan saat pemilu. Di Tasikmalaya, fenomena ini muncul dalam bentuk dukungan politik yang disalurkan melalui jaringan pesantren. Mobilisasi masyarakat bisa dilakukan melalui pengajian, majelis taklim, dan kegiatan pendidikan. Hal ini menjadikan pesantren sebagai aktor penting dalam perhitungan politik lokal, bahkan meski tidak terlibat secara langsung.Selain berperan dalam bidang sosial dan politik, banyak pesantren di Tasikmalaya mengembangkan kemandirian ekonomi. Mereka membangun unit usaha, koperasi, pertanian, atau usaha kecil yang mendukung ekonomi santri dan masyarakat sekitar. Kemandirian ekonomi ini menjadikan pesantren lebih kuat karena tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan negara. Dari perspektif geopolitik, kondisi ini penting karena komunitas yang mandiri lebih mampu menjaga stabilitas sosial dan lebih tahan terhadap pengaruh luar yang berpotensi mengganggu.Menariknya, kontroversi terbaru terkait penolakan sebagian ormas Islam Tasikmalaya terhadap konser musik seperti band Hindia menunjukkan bagaimana identitas keagamaan dan otoritas sosial lokal dapat memengaruhi keputusan publik. Polemik tersebut bukan sekadar perbedaan selera hiburan, tetapi menggambarkan benturan nilai antara identitas lokal dan budaya populer yang masuk melalui arus globalisasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan memiliki daya tawar sosial yang nyata bahkan mampu membentuk ruang budaya kota. Dalam kacamata Colin S. Gray, inilah contoh bagaimana aktor non-negara mengelola dan mempengaruhi “ruang” melalui otoritas moral dan legitimasi sosial.Kontroversi ini juga menguatkan argumen bahwa pesantren dan otoritas keagamaan bukan sekadar institusi keagamaan, melainkan aktor geopolitik lokal yang mempengaruhi arah kebijakan informal, persepsi publik, dan batasan-batasan sosial yang berlaku di masyarakat. Ketika nilai global bertemu dengan identitas lokal, pesantren dan ormas sering menjadi penengah, pengarah, atau bahkan “penentu” narasi yang dominan.Namun, pesantren juga menghadapi tantangan baru, terutama dari perkembangan teknologi digital. Ruang digital membawa masuk beragam narasi, termasuk narasi keagamaan transnasional, informasi yang belum terbukti kebenarannya, dan konten yang berpotensi memecah belah. Tantangan ini menunjukkan bahwa geopolitik tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga ruang informasi. Jika pesantren tidak memperkuat literasi digital, masyarakat bisa menjadi sasaran mudah bagi narasi negatif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital menjadi kebutuhan strategis bagi pesantren hari ini.Melihat peran yang besar ini, kebijakan pembangunan di Tasikmalaya perlu memasukkan pesantren sebagai bagian dari aktor strategis. Pemerintah lokal bisa membangun kerja sama dengan pesantren untuk mendukung program pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Pesantren harus dipandang bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai partner yang memiliki jaringan dan pengaruh yang kuat. Selain itu, pembangunan infrastruktur atau kebijakan sosial akan lebih efektif jika mempertimbangkan pola budaya dan struktur otoritas lokal yang sudah ada di masyarakat.Kurikulum pendidikan pesantren juga perlu dikembangkan agar lebih kontekstual. Selain memperkuat pendidikan keagamaan, pesantren sebaiknya memberikan materi literasi digital, dasar-dasar geopolitik, dan pengetahuan ekonomi lokal. Dengan begitu, santri dapat memahami tantangan zaman dan mampu berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan identitas daerah.Secara keseluruhan, pesantren Tasikmalaya adalah bagian penting dari struktur kekuatan lokal. Mereka membentuk identitas, mempengaruhi perilaku politik, menjaga stabilitas sosial, dan berperan dalam ekonomi masyarakat. Sayangnya, peran besar ini sering tidak masuk dalam perencanaan kebijakan atau diskusi geopolitik. Padahal, dalam konteks geopolitik modern seperti yang dijelaskan oleh Colin S. Gray, aktor lokal seperti pesantren justru memiliki pengaruh strategis karena mampu menggerakkan komunitas dari bawah.Mengabaikan pesantren berarti mengabaikan kekuatan sosial yang nyata. Sebaliknya, mengakui dan mengoptimalkan peran mereka berarti memperkuat fondasi geopolitik daerah. Di era global dan digital ini, pesantren mampu menjadi penjaga identitas, tempat solidaritas sosial, dan partner utama dalam pembangunan Tasikmalaya.